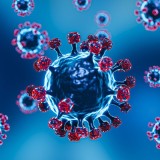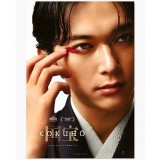TIMES BALI, BALI – Setiap akhir Oktober, suasana di sekolah-sekolah berubah. Spanduk bertuliskan Selamat Hari Sumpah Pemuda digantung di depan kelas, para guru sibuk menyiapkan upacara, dan murid-murid berdiri tegak membaca teks yang sama: Kami putra dan putri Indonesia.
Suara mereka lantang, tapi entah mengapa ada yang terasa hampa. Seolah kata-kata itu hanya bergema di udara tanpa menyalakan apa-apa di dada. Kita membaca sumpah yang sama setiap tahun, tapi tak selalu mengerti untuk apa ia dulu diucapkan.
Padahal, Sumpah Pemuda bukan sekadar peristiwa sejarah dengan tiga kalimat legendaris. Ia adalah momen kesadaran kolektif. Tahun 1928, para pemuda dari berbagai organisasi-Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Celebes bertemu bukan untuk berpesta, tapi untuk membayangkan sesuatu yang belum ada: Indonesia.
Mereka hidup di zaman ketika kata “Indonesia” bahkan belum punya bentuk politik. Tapi di tengah perbedaan bahasa, budaya, dan asal-usul, mereka punya keberanian untuk berkata: kita satu.
Mereka tidak hanya bersatu dalam tataran geografis, tapi bersatu dalam imajinasi-membayangkan sebuah rumah bersama yang masih berupa ide. Hari ini, kita mengenang mereka lewat upacara. Tapi sayangnya, banyak yang berhenti di situ.
Sekolah-sekolah mengajarkan tanggal dan tokoh, tapi jarang mengajak murid menyelami makna. Seolah Sumpah Pemuda hanyalah hafalan, bukan pengalaman. Anak-anak tahu isi sumpahnya, tapi tidak tahu mengapa ia lahir dari nyali yang begitu besar.
Ki Hadjar Dewantara pernah menulis bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, lahir dan batin. Merdeka berarti berani berpikir, bukan hanya patuh pada kunci jawaban. Tapi di ruang-ruang kelas kita hari ini, kemerdekaan berpikir justru makin jarang tumbuh.
Murid diajarkan mencari “jawaban benar”, bukan pertanyaan baru. Mereka diminta seragam, bukan berbeda. Di titik ini, semangat “kami bersatu” dari 1928 berubah pelan menjadi “kami seragam agar diterima.”
Padahal, keberanian untuk berpikir berbeda itulah yang membuat para pemuda 1928 istimewa. Mereka menolak kenyataan yang dibentuk penjajahan. Mereka mencipta peta baru: Indonesia.
Bukankah pendidikan seharusnya juga begitu-sebuah ruang untuk memberontak secara intelektual? Tempat murid bukan hanya menghafal, tapi menafsir. Tempat perbedaan tidak dimatikan, tapi dirayakan.
Dari Kolonialisme Fisik ke Kolonialisme Digital
Zaman berubah, medan perjuangan pun bergeser. Kalau dulu penjajahan datang dari kapal dan senjata, sekarang penjajahan datang lewat layar dan algoritma. Kita hidup di tengah arus informasi yang deras, tapi sering kehilangan arah.
Anak muda sekarang bisa mengakses dunia dari genggaman, tapi juga bisa kehilangan dirinya di dalamnya. Bahasa Indonesia tergeser oleh bahasa tren; nilai-nilai lokal kalah oleh gaya hidup global. Ini bentuk penjajahan yang lebih halus-penjajahan selera, cara berpikir, dan standar kebahagiaan.
Di sinilah semangat Sumpah Pemuda perlu dibaca ulang. Ia bukan hanya sumpah untuk menyatukan bangsa, tapi juga kesadaran untuk menemukan jati diri di tengah zaman yang terus berubah. Menjadi Indonesia hari ini bukan berarti menolak modernitas, tapi belajar menegosiasikannya. Menjadi bagian dari dunia, tanpa kehilangan akar.
Sayangnya, nasionalisme kita kini sering berhenti pada spanduk dan slogan. Kata “nasionalisme” ramai disebut di lomba pidato, tapi jarang terasa di keseharian. Sekolah bicara tentang karakter Pancasila, tapi sistemnya masih mengukur manusia dari angka ujian.
Padahal, nasionalisme sejati bukan sekadar cinta tanah air, melainkan kesadaran reflektif: kesediaan untuk memahami dan menghormati perbedaan. Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa kebangsaan lahir bukan dari keseragaman, tapi dari pertemuan lintas perbedaan.
Bayangkan jika pelajaran sejarah di sekolah tidak lagi berhenti pada hafalan kronologi, tetapi menjadi ruang dialog. Anak Jawa belajar tentang musik Batak. Siswa Papua berbagi cerita dengan teman dari Madura. Mereka saling mengenal, saling memahami, dan bersama mencari makna baru dari kata “Indonesia.”
Itulah pendidikan yang benar-benar menyalakan api Sumpah Pemuda-pendidikan yang memerdekakan, bukan menghafalkan.
Menuju Sumpah Pemuda Digital
Kini, zaman digital memberi peluang baru. Satu unggahan di media sosial bisa menggugah ribuan orang. Satu video bisa menumbuhkan solidaritas lintas daerah. Tapi kekuatan itu sering terbuang percuma dalam perdebatan sia-sia, polarisasi, dan ujaran kebencian.
Bagaimana kalau kita punya versi baru dari Sumpah Pemuda-bukan di aula kongres, tapi di dunia maya? Bayangkan jika generasi muda berkata, “Kami pengguna internet Indonesia, berjanji menjaga ruang digital yang sehat, beradab, dan berakal.”
Sumpah Pemuda digital bukan hanya soal kebanggaan nasional, tapi juga kesadaran digital: berpikir kritis di tengah banjir informasi, menghormati perbedaan di kolom komentar, dan menjaga empati di tengah dunia yang makin bising.
Pendidikan hari ini harus berani menyiapkan generasi semacam itu-bukan sekadar pengguna teknologi, tapi pengelola makna. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil: dari keberanian untuk berkata “kami satu”, di saat dunia justru memisahkan.
Tantangan kita sekarang bukan lagi membebaskan Indonesia dari penjajah, tapi membebaskannya dari lupa. Lupa bahwa Indonesia pernah lahir dari dialog, bukan monolog. Dari keberanian untuk membayangkan yang belum ada.
Maka tugas pendidikan hari ini bukan sekadar mengajarkan sejarah, tetapi menyalakan ulang kesadaran. Membaca ulang masa lalu, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menemukan arah baru.
Soekarno pernah berkata, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah.” Tapi mungkin perlu kita tambahkan: bangsa yang benar-benar hidup adalah bangsa yang belajar dari sejarah untuk menulis masa depannya sendiri.
Sumpah Pemuda bukan sekadar teks di dinding ruang kelas. Ia adalah api yang menunggu dinyalakan lagi di dada generasi baru-yang berani berpikir bebas, bersatu tanpa seragam, dan mencintai Indonesia bukan karena diwajibkan, tapi karena dipahami.
Pendidikan sejati bukan tentang berapa banyak pelajaran yang kita hafal, tapi seberapa dalam kita sadar untuk menjadi manusia Indonesia dengan kepala yang terbuka, hati yang merdeka, dan cita-cita yang tak pernah padam. (*)
***
*) Oleh : Saiful Bahri, M. Pd., Praktisi Pendidikan dan Guru MA Unggulan Cahaya Cendekia, Jimbaran, Badung, Bali.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |